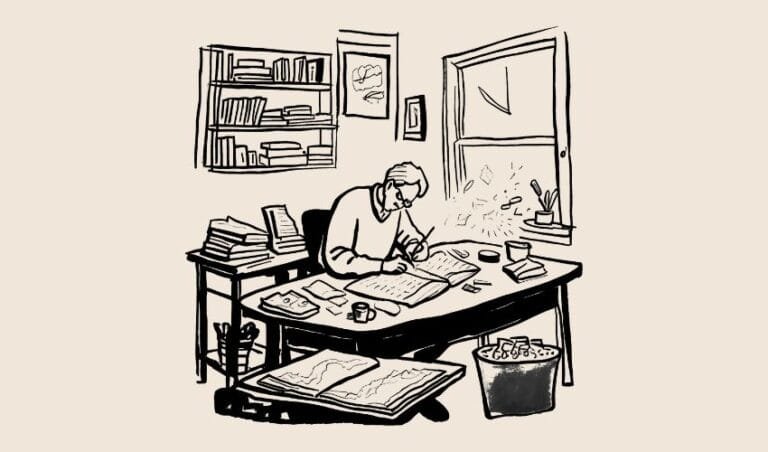Seperti barang baru yang tidak pernah ada sama sekali sebelumnya, yakni term islam Nusantara. Kehadiran term tersebut kemudian cukup memantik perhatian dari beberapa kalangan. Bahkan tidak sedikit yang menentangnya. Karena dianggap bahwa term tersebut dapat berpotensi memberikan pemahaman yang salah tentang nasab pengetahuan tentang agama islam. Sebab dalam khazanah pemikiran Islam sendiri term tersebut sama sekali asing untuk dikenal. Akhirnya, terjadi pemutarbalikan dan anggapan-anggapan yang melahirkan sikap penolakan atas term yang dianggap kontroversi. Lain daripada itu, term Islam Nusantara tidak dibentuk untuk kemudian menegasikan satu golongan tertentu yang berbeda dalam segala aspeknya. Kemunculan term ini tidak pula memiliki tujuan politis. Begitu rawan dan melahirkan cukup banyak reaksi setelah term ini lahir. Dikarenakan belum adanya kesamaan pemahaman tentang nilai Substansi.
Terdapat satu hal yang perlu ditegaskan sebagai prolog dalam konteks term Islam Nusantara, bahwa yang dimaksud term tersebut, adalah islam di Nusantara. Agar satu dan yang lain tidak jatuh dalam persepsi tunggal. Islam di Nusantara merupakan nilai-nilai universal islam yang telah diimplemetasikan di bumi Nusantara sejak dalam kurun masa yang lama oleh para pendahulu di Nusantara ini. Salah satu ciri yang dapat direkam dari garis sejarah bahwa, islamisasi di bumi Nusantara dilakukan dengan santun dalam menyebarkan agama, menjunjung tinggi nilai moderat dengan penuh toleransi, menjunjung tinggi hak-hak perempuan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya.
Mengingat islam sebagai agama rahmatan lil alamin, tentu hal tersebut perlu wujud nyata dalam bentuk kongkret yang menguatkan statement tersebut. Seperti halnya di Indonesia sebagai negara yang majemuk, di mana pluralitas menjadi satu hal yang niscaya keberadannya. Indoensia yang berpenduduk lebih dari 250 juta, didiami oleh 700-an suku bahasa, 500-an bahasa, ragam tradisi dan budaya. Penerapan nilai-nilai islam di Nusantara memungkinkan tidak sama. Katakanlah bahwa setiap tradisi dari satu wilayah dengan wilayah yang lain pun berbeda. Maka sikap penyesuaian di sini menjadi kebutuhan pokok untuk dilakukan lantaran adanya keberagaman yang dipandang sebagai sebuah kekayaan yang perlu dijaga agar menjadi semacam mutiara yang bernilai mahal, harkat dan martabanya. Sebutlah ketika nilai-nilai islam terkait dengan penyikapan terhadap perempuan.
Penghormatan terhadap perempuan sangat mungkin tidak sama ekspresinya antara satu tempat dengan tempat lain. Sikap Islam dengan ajarannya yang rahmatan lil alamin, harus menunjukkan buktinya kepada sesuatu eksternal di luarnya. Jika mungkin perbedaan akan mengarah tajam kepada akidah atau keyakinan sekalipun, ia haruslah memberi ruang atas kenyataan tersebut. Maka term Islam di Nusantara hendak menunjukkan bahwa ia lahir dari proses yang panjang dalam sejarah. Membentuk kristal di kemudian hari dengan bentuknya yang khas yakni, islam didakwahkan di Nusantara dengan cara merangkul, menyelaraskan, menghormati, dan tidak memberangus budaya. Sebab hal ini menjadi konsekuensi logis dari ajaran Islam yang syumul (sempurna) (baca Abu Yasid: Islam Moderat, 2018). Artinya bahwa Islam turun dari langit idealisme menuju bumi yang realitas. Maka bukan tidak mungkin ajaran islam tidak dapat diterapkan dengan sempurna. Justru kesempurnaan itu dilihat dengan tetap memiliki spirit idealitas dan tidak menutup sebelah mata terhadap realitas (baca Afifuddin Muhajir: Fiqh Tata Negara).
Kilas balik dalam sejarah, wali songo menjadi role model yang dapat dikatakan sangat arif dan bijaksana di dalam menyebarkan islam di Nusantara. Sebutlah kanjeng Sunan Kalijaga dengan seni pewayangannya. Saat pertama kali menginjakkan telapak perjuangannya, Sunan Kalijaga menapak tilasi tanah Pajajaran hingga Majapahit sebagai seorang dalang. Profesi sebagai dalang, menjadi salah satu tanda kesadaran akan keilmuan sunan kalijaga yang begitu syumul (sempurna). Ia menyadari bahwa, sebelum melakukan islamisasi di tanah Nusantara, ia perlu membaca bangunan kultur yang telah ada dan mengakar dalam adat masyarakat setempat. Setelah pembacaan yang sempurna, barulah strategi penyesuaian dlilakuan. Dakwah nilai-nilai islam, kemudian dikemas dalam balutan kesenian yang indah, yaitu perwayangan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam pertunjukannya, Sunan Kalijaga melakukan rekonstruksi alur dan kisah dalam setiap plot cerita yang dikisahkan, dengan menyisipkan nilai-nilai keislaman. Seperti di antaranya berkisah tentang seorang nabi Khidir yang kemudian dikenalkan dengan sebutan, Dewa Ruci. Kisah lain bertajuk, Jimat Kalimasada (kalimat syahadat).
Tokoh akademisi seperti Agus Sunyoto dalam atlasnya (buku: Atlas Wali Songo) menyampaikan hal tersebut menjadi salah bukti keluasan ilmu dan kematangan aspek emosional Sunan Kalijaga, sebagai seorang pendakwah. Ia tidak serta merta melakukan tindakan tegas dan frontal, menolak dan meruntuhkan suatu kebiasaan yang telah ada, seperti seni di tengah-tengah masyarakat. Melainkan, dengan kecerdasannya, ia membaca bahwa seni, dapat menjadi sebuah jendela kecil untuk menampilkan islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan Sunan Kalijaga melakukan daur ulang bentuk-bentuk wayang yang ditampilkan. Tentu hal ini menjadi tinta emas dalam sejarah intelektual persebaran islam di Nusantara, dan menjadi satu bukti pada masa-masa berikutnya hingga sekarang, bahwa islam, bukan hanya sebuah agama dengan nilai dogmatisasinya yang dikenal jumud dan stagnan, melainkan dalam ajaran islam, terdapat pula sebuah nilai fleksibilitas dalam hal-hal yang berkenaan dengan prinsip wasaiiliyyah (sarana dan prasarana), furuiyyah (sesuatu yang bersifat cabang dalam persoalan agama). Sebab tidak sedikit beberapa orang bahkan tokoh orientalis yang menilai islam, sebagai agama yang tidak inklusif terhadap pembaharuan-pembaharuan, stagnan, dan lain-lain. Kegagalan dalam memahami islam antara, mana hal-hal yang bersifat wasailiiyah, furuiyyah, dan mana persoalan-persoalan yang menyangkut ushuliyyah (sesuatu yang pokok dan fundamental dalam agama) yang tidak dapat ditawar-menawar. Kebijaksanaan Sunan Kalijaga dengan gaya berislamnya dalam dakwah. Demikian islam di Nusantara dengan distingsi adat dan kultur budayanya.
Surabaya.
Penulis: Abd. Shovy